
Najib Burhani
I received my PhD in Religious Studies, with emphasis on sectarian movements in Islam and religious minorities with Islamic origin such as Ahmadiyya, Druze, Isma'ili, Yazidi, and Baha'i Faith, from University of California- Santa Barbara. Currently I am a researcher at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Indonesia. Among my publications are Muhammadiyah Jawa (2010), 'Tarekat' tanpa Tarekat (2002), Sufisme Kota (2001), and Islam Dinamis (2001).
Supervisors: Juan E. Campo, R. Stephen Humphreys, Mark Juergensmeyer, and Ahmad Atif Ahmad
Supervisors: Juan E. Campo, R. Stephen Humphreys, Mark Juergensmeyer, and Ahmad Atif Ahmad
less
Related Authors
Muqtedar Khan
University of Delaware
Armando Salvatore
McGill University
Martin van Bruinessen
Universiteit Utrecht
Armando Marques-Guedes
UNL - New University of Lisbon
Michael W Charney
SOAS University of London
Moch Nur Ichwan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Thongchai Winichakul ธงชัย วินิจจะกูล
University of Wisconsin-Madison
Carole Cusack
The University of Sydney
Andrea Acri
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Alexander Wain
University of St Andrews
InterestsView All (8)



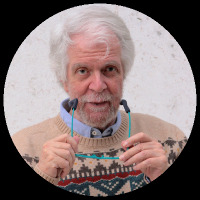


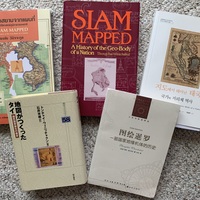



Uploads
Books by Najib Burhani
Penutupan lokalisasi tersebut berkait kelindan dengan beberapa isu, diantaranya adalah: ekonomi,pembangunan dan tata ruang kota, moralitas, serta kesehatan masyarakat. Dalam hal ekonomi dan pembangunan kota, Pemkot Surabaya berencana untuk meningkatkan nilai ekonomi kota melalui pembangunan jalan, kawasan perdagangan dan pusat industri rumah tangga yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan mengenai wilayah Dolly dan Jarak. Secara moral, adanya lokalisasi dianggap merusak tatanan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Sedangkan secara kesehatan masyarakat, lokalisasi dianggap sebagai pusat penularan penyakit kelamin.
Lokalisasi merupakan tempat suatu kota atau desa yang bertemakan seksualitas. Jasa yang ditawarkan di lokalisasi bisa beragam, tidak hanya terbatas pada bentuk prostitusi atau PSK. Beberapa bisnis lain yang berada di kawasan lokalisasi adalah panti pijat, perdagangan alat untuk seks, salon kecantikan, pub dan minum-minuman keras dan tempat parkir. Meskipun disebut sebagai lokalisasi, namun semua lokalisasi di Surabaya secara lokasi tidak terpisah dari perumahan penduduk. Tidak ada tembok yang memisahkannya dengan masyarakat sekitar. Bahkan lokalisasi itu tidak jauh dari beberapa Sekolah Dasar (SD), musholla, masjid dan gereja. Tempat tinggal PSK dan keseluruhan aktivitasnya pun menyatu dengan masyarakat sekitar. Jika mengacu pada definisi lokalisasi, maka "Berbagai tempat prostitusi di Surabaya tidak bisa disebut sebagai lokalisasi". Tempat yang dapat dikatakan sebagai lokalisasi adalah Kramat Tunggak di Jakarta yang kini telah ditutup.
Dengan mengacu pada teori Lavebvre, maka lokalisasi di Surabaya itu terjadi dengan sendirinya sebagai tempat orang untuk mempresentasikan dirinya (space of representation), bukan sebagai tempat yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan atau kegiatan tertentu (representation of space). Lokalisasi itu terbentuk dengan sendirinya melalui aktivitas sehari-hari yang dimulai dari satu wisma yang kemudian berkembang terus menjadi banyak. Ini yang disebut Lavebvre sebagai proses pemaknaan space atau the production of space.
• Of these two mainstream organizations, Muhammadiyah is often perceived to be the more conservative one. This organization is seen to be closer and showing more affinity to Islamist groups. On political issues, for instance, Muhammadiyah was still steered by Islamist imagery of the ruling based on religion or the dominance of Muslim in Indonesia.
• Despite several efforts to introduce new perspectives, on cultural issues, Muhammadiyah is often guided by its old principle on the enmity towards, what is called, the TBC (takhayul, bid’ah and churafat; delusions, religious innovation without precedence in the Prophetic traditions and the Qur’an, and superstitions or irrational belief). This position has placed Muhammadiyah in an uneasy relationship with local culture and also traditionalist Islam.
• The three issues that occurred in 2017 --the banning of the HTI, the recurrent controversy on the PKI, and the ruling of the Constitutional Court on Penghayat Kepercayaan-- fall within the cultural spectrum of Muhammadiyah’s standing. They are the issues where Muhammadiyah has a shaky position, becoming easily drawn into Islamist and conservative tendencies.
• Despite the conservative political and cultural accusation, Muhammadiyah does not change from its raison d’être as a social movement with strong emphasis on social services and guided by its long-held theology of al-Mā`ūn (kindness).
• It is the theology of al-Mā’ūn that has been able to prevent Muhammadiyah from dwelling on mythical or abstract issues and neutralize Muhammadiyah from Islamist inclination. It brings the members of Muhammadiyah to become more realistic in seeing the world, distance themselves from the utopic vision of caliphate, the dream of sharia as the Messiah that will solve every problem, or the temptation to create an Islamic state.
• The theology of al-Mā’ūn has directed Muhammadiyah into adopting “pragmatic Islamism”. It is an Islamism that communicates with the dynamics in society or which experiences social dynamics.
● Undermining the teachings and ideology of radicalism seems to be more complicated than direct armed confrontation. Killing terrorist does not always mean killing terrorism. It could even have the opposite impact, i.e. strengthening and fertilizing the radical ideology. It is for the purpose of countering the ideology of terrorism and domesticating radicalism that the government supported NU (Nahdlatul Ulama) in promoting Islam Nusantara, widely believed to be the ideological antidote for radicalism and terrorism.
● Proponents of Islam Nusantara believe that radical ideology is against the characters of Islam Nusantara, i.e. peaceful, smiling, tolerant, moderate, and accommodative to culture. The radical and intolerant ideology are commonly seen in NU circle as brought and disseminated by trans-national movements, such as Hizbut Tahrir and Salafi-Wahhabi groups. They are not terrorist groups, but they teach intolerant and exclusive religiosity which provide a breeding ground for terrorism.
● Within Indonesian Muslims, including NU, Islam Nusantara has received various responses and resistance. The emergence of NU Garis Lurus and the concerted efforts to debunk Islam Nusantara by some preachers are among the forms of activities to undermine Islam Nusantara.
● The introduction of Islam Nusantara is further hampered by the attitude of some of its proponents who emphasize the exclusivity of this brand by identifying Islam Nusantara only with NU and neglecting other Islamic movements. Sometimes, they tend to become reductionist and revisionist in seeing Indonesian Islamic history.
● Barring its current limits, Islam Nusantara has a potential to become an exceptional Islam or a template of tolerant Islam that can be emulated by other Muslims in the world. This particularly with its ability to accommodate local culture and to live in a multicultural society.
Proses perpindahan dari keyakinan keagaman tertentu ke keyakinan lain, menurut William James, pakar psikologi ternama dari Amerika Serikat yang hidup tahun 1842 – 1910, disebut sebagai proses conversion. Proses ini tidak melulu berarti perpindahan dari agama tertentu ke agama lain seperti dari Kristen ke Islam dan dari Hindu ke Kristen, tapi juga mencakup perpindahan dari kelompok agama tertentu ke kelompok agama lain, seperti dari Sunni ke Syiah dan dari Jesuit ke Mormon. Bahkan, perpindahan dari seorang yang sebelumnya merupakan penganut agama atau beriman menjadi seorang ateis atau sebaliknya adalah termasuk dalam kategori conversion.
Pertanyaannya, apakah perpindahan dari seseorang yang secara kultural adalah pengikut NU (Nahdlatul Ulama) menjadi aktivis Muhammadiyah bisa disebut sebagai proses konversi juga? Jika mengikuti William James, maka jawaban dari pertanyaan adalah bisa “ya” dan bisa juga “tidak”. Ini tentu mengacu pada definisi dari kata konversi itu sendiri. Dalam buku klasiknya yang berjudul The Varieties of Religious Experience (1985), William James mendefinikan konversi sebagai sebuah proses dimana “religious ideas, previously peripheral in his consciousness, now take a central place, and that religious aims form the habitual centre of his energy” (h. 196). Artinya, konversi itu terjadi jika suatu pandangan keagamaan yang dulunya hanya dianggap pinggiran dan tak penting atau bahkan menyimpang oleh seseorang, namun kemudian ia berubah menjadi meyakini bahwa yang pinggiran itu menjadi sentral atau sangat penting, maka orang itu telah mengalami apa yang disebut proses konversi. Apalagi jika keyakinan baru menjadi tempat ia menumpahkan seluruh aktivitas dan energinya.
Mengikuti definisi yang dikembangkan oleh James itu, maka beberapa kasus perpindahan dari NU ke Muhammadiyah atau sebaliknya bisa masuk kategori konversi dan bisa juga sekadar perpindahan organisasi. Arifin Ilham, da’i selebritis dan pelopor dzikir berjamaah, bisa menjadi contoh konversi model ini. Ia berasal dari keluarga Muhammadiyah dan mendapat pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Pada masa mudanya Arifin Ilham adalah orang yang benci dan antipati terhadap dzikir. Ia, misalnya, pernah mengatakan kepada orang-orang yang berdzikir bahwa “Mereka itu ahli neraka. Zikir pake dikerasin segala, ramai-ramai lagi” (Mintarja 2004, 41). Namun kini Arifin Ilham menjadi orang yang memilih dzikir sebagai paradigm hidup dan sesuatu yang paling sentral dalam hidupnya. Contoh sebaliknya, konversi dari non-Muhammadiyah ke Muhammadiyah, barangkali bisa dilihat dari kasus Ketua Umum Muhammadiyah saat ini, yaitu Din Syamsuddin.
Berbeda dari kasus Arifin Ilham, banyak sekali orang yang menjadi Muhammadiyah karena dia diangkat menjadi guru atau dosen atau tenaga medis di lembaga milik Muhammadiyah. Ada juga yang menjadi Muhammadiyah karena sekolah di Muhammadiyah. Tentu saja tak semua orang itu bisa disebut mengalami konversi. Mereka yang tak mengalami transformasi spiritual tak akan masuk kategori konversi. Mereka masuk kategori kedua, yaitu hanya “menjadi” (becoming) Muhammadiyah. Beberapa diantara mereka bisa jadi sama sekali tak memahami ideologi Muhammadiyah dan secara ritual berbeda dari apa yang umum dilakukan di Muhammadiyah. Kelompok ini barangkali tak perlu dipermasalahkan selama mereka tetap profesional dalam pekerjaannya dan tidak mengganggu aktivitas Muhammadiyah.
Yang merepotkan adalah mereka yang ada di dalam amal usaha Muhammadiyah namun tak pernah menjadi Muhammadiyah dan justru sebaliknya mereka menjadi ancaman bagi Muhammadiyah. Kelompok ketiga ini mungkin bisa disebut sebagai “Muhammadiyah palsu” atau “fake Muhammadiyah”. Kasus tahun 2006 dan 2007 ketika Muhammadiyah melakukan “disiplin organisasi” dengan mengeluarkan SK 149/2006 dan SK 101/2007 bisa menjadi contoh (Burhani 2013). Tentu saja ada berbagai alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Kita tak hanya perlu menengok hal ini sebagai ancaman dari luar, tapi juga bisa dilihat sebagai kekurang berhasilan proses pengkaderan di internal Muhammadiyah.
Bentuk terakhir adalah mereka yang tidak sekadar “menjadi Muhammadiyah”, tapi “menjadi aktivis Muhammadiyah” namun dengan tetap membawa gerbong pemahaman dan pemikiran yang sebelumnya dimiliki oleh orang tersebut. Mereka yang masuk dalam kategori ini sangat banyak dan, meminjam istilah dari Abdul Munir Mulkhan dan Abdul Mukti, mereka inilah yang kemudian menjadi dasar dari kelompok yang disebut sebagai Marmud (Marhaen-Muhamadiyah), MuNU (Muhammadiyah-NU), Kris-Muha (Kristen-Muhammadiyah), dan sebagainya. Keberadaan kelompok ini bisa memperkaya warna Muhammadiyah dan menghidupkan gerakan pemikiran di organisasi ini jika dikelola dengan baik. Dan tentu saja jika Muhammadiyah ingin menjadi organisasi yang kosmopolit, ia harus siap menerima orang dengan latar belakang yang sangat beragam.
Karena Din Syamsuddin tidak lagi menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka barangkali ini saat yang tepat untuk membicarakan legacy atau karya unggulan yang ia wariskan kepada organisasi modernis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang berdiri tahun 1912 ini. Tentu saja ada catatan yang sering disebut sebagai kekurangannya selama sepuluh tahun (2005-2015) memimpin Muhammadiyah, misalnya kurang berhasilnya organisasi ini dalam menempatkan kader-kader terbaiknya dalam birokrasi pemerintahan. Namun tulisan ini khusus melihat apa saja warisan dan prestasi dari Din Syamsuddin yang patut dilanjutkan oleh para penerusnya di Muhammadiyah.
Globalisasi sering dipahami sebagai proses penyatuan dunia dimana waktu, jarak dan tempat bukan lagi persoalan dan ketika setiap hal dan setiap orang di bumi ini terkait satu sama lain. Ada empat pergerakan utama dalam globalisasi, yaitu: barang dan layanan, informasi, orang, dan modal. Perpindahan keempat hal tersebut dari satu negara ke negara lain memang telah terjadi sejak dahulu kala. Namun perpindahan dengan sangat cepat hanya terjadi setelah revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi pada beberapa dekade belakangan ini. Akibat dari revolusi itu, dimensi jarak dan waktu menjadi semakin kabur dan sedikit demi sedikit menghilang.
Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini menyebabkan masyarakat secara mudah mengakses informasi dari luar ataupun berinteraksi secara intens dalam sebuah ruang global. Ketika ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) mendeklarasikan kekhilafahan dibawah Abu Bakar al-Baghdadi, kita dikejutkan dengan adanya sejumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan mereka di Timur Tengah dan sebagian dari mereka merekrut anggota di Indonesia serta melakukan baiat di UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta. Ketika konflik Sunni dan Syiah terjadi di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti-Syiah seperti dalam bentuk ANNAS (Aliansi Nasional Anti-Syiah).
Globalisasi juga menyebabkan Trans-National Capitalist Network (TNC) masuk dalam kehidupan masyarakat dan menyedot kekayaan yang mestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Bekerjasama dengan ‘komprador’, para kapitalis global itu menciptakan jurang yang begitu lebar antara mereka yang kaya dan miskin seperti terjadi di daerah penambangan Freeport di Papua.
Filosofi yang mendasari globalisasi adalah asimilasionisme. Dalam filosofi ini, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Makanya, dalam globalisasi budaya, salah satu dampaknya adalah homogenisasi. Ini, misalnya, terwujud dalam bentuk McWorld atau McDonaldization. Contoh lainnya adalah memandang Islam secara homogen dengan mengidentikkannya dengan Arab dan Arabisasi.
Islam Nusantara
Homogenisasi ini tentu tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Respon balik atau resistensi terhadap homogenisasi ini diantaranya dalam bentuk indigenization. Islam Nusantara yang dipopulerkan anak-anak NU dan menjadi tema Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus nanti adalah satu bentuk respon terhadap globalisasi dengan melakukan indigenisasi.
Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu kepada Islam ala Indonesia yang otentik; langgamnya Nusantara, tapi isi dan liriknya Islam; bajunya Indonesia, tapi badannya Islam. Ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan “pribumisasi Islam” yang pernah dipopulerkan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan resmi nama ini diantaranya adalah dalam Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 26 tahun 2008.
Munculnya Islam Nusantara adalah bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai “paradoks globalisasi”. Dalam istilah TH Erikson (2007, 14), “Semakin orang mengglobal seringkali dia menjadi semakin terobsesi dengan keunikan budaya asalnya.” Dalam kalimat ilmuwan lain, “ketika dunia semakin global maka perbedaan-perbedaan kecil antar umat manusia itu semakin ditonjolkan” (Ang 2014, 10). Banyak yang menduga bahwa semakin kita mengenal dunia luar dan kelompok yang berbeda, maka kita menjadi semakin terbuka. Namun seringkali yang terjadi tidak sejalan dengan logika itu. Di tengah globalisasi, banyak orang yang semakin fanatik dan tidak menerima perbedaan serta pluralitas. Ini misalnya terjadi dalam beberapa pilkada yang “mengharuskan” putra daerah yang dipilih. Dalam konteks dunia, justru di era globalisasi ini hampir setiap tahun kita melihat kemunculan negara baru dalam keanggotaan PBB.
Tentu saja respon terhadap globalisasi dalam bentuk “Islam Nusantara” adalah pilihat terbaik dibandingkan dengan penolakan total atau penerimaan total. Dalam merespon terhadap globalisasi, terutama yang datang dari Barat, beberapa kelompok agama justru mencari perlindungan dalam homogenitas dan eksklusivitas kelompoknya. Sepertinya kedamaian itu bisa terjadi dengan menolak keragaman atau sesuatu yang asing. Di tengah globalisasi, banyak orang yang mencoba menutup diri dan menghalangi orang yang berbeda hadir di tengah masyarakat. Fenomena munculnya perumahan atau cluster perumahan eksklusif untuk komunitas agama tertentu adalah misal. Bahkan kuburan/ pemakaman dan rumah kos pun kadang dibuat untuk pengikut agama tertentu. Respon terhadap globalisasi yang lebih buruk lagi tentu saja seperti dalam bentuk redikalisme dan terorisme. Islam Nusantara bisa menjadi respon yang sangat baik terhadap globalisasi jika ia tidak mengarah kepada parokhialisme dan sektarianisme.
Islam Berkemajuan
Respon lain terhadap globalisasi ditampilkan oleh Muhammadiyah dengan slogan “Islam berkemajuan”. Sebelum tahun 2009, slogan ini jarang terdengar bahkan di kalangan Muhamadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul Islam Berkemajuan: Kyai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kyai Syuja’ (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kyai Dahlan ini diantaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah. Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah “Islam berkemajuan”. Pada Muktamar di Yogyakarta tahun 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter ke-Islaman Muhammadiyah.
Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai “Islam kosmopolitan”, yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional” (Tanfidz Muhammadiyah 2010, 18). Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur-tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang otentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan karakter Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana bagi untuk dialog antar peradaban.
Ringkasnya, kelahiran dari slogan “Islam Nusantara” dan “Islam berkemajuan” memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada tahun 1920-an. Ketika itu, sebagai respon terhadap berbagai peristiwa di Arabia dan Turki (comite chilafat dan comite hijaz), maka lahirlah NU. Sementara Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi Kristen, pemikiran Abduh, dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam Déjà vu.
Sebagai sebuah sistem pemerintahan, khilafah telah hancur pada Maret 1924 setelah sistem ini berjalan lebih dari 13 abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad tahun 632 Masehi. Namun sebagai wacana, gagasan untuk membangun kembali khilafah itu terus muncul dalam tubuh sebagian umat Islam. Tahun 2007 lalu, misalnya, Universitas Meryland mengadakan survey terhadap 4.384 orang Islam di empat negara (Maroko, Mesir, Pakistan, dan Indonesia). Salah satu pertanyaannya adalah pandangan mereka tentang khilafah. Mereka yang memberikan jawaban “sangat setuju” (agree strongly) dan “agak setuju” (agree somewhat) adalah sebagai berikut: Mesir (67%), Indonesia (49%), Maroko (71%), dan Pakistan (67%). Selain HT dan Al-Qaida, salah satu promoter wacana khilafah adalah Abul A’la Maududi (1903-1979) yang, misalnya, menyebutkan bahwa khilafah adalah salah satu dari tiga prinsip politik Islam, yaitu tauhid, risalah (kenabian), dan khilafah (Maududi tt.; Liebl 2009, 373-4).
Dalam wacana tentang khilafah ini, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kalau Ahmadiyah diakui sebagai bagian dari Islam, maka sistem kekhilafahan Islam itu sebetulnya tidaklah benar-benar hancur. Ini karena sebelum kekhilafahan Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk, pada tahun 1908 kelompok Ahmadiyah telah mendirikan kekhilafahan baru di India. Hanya saja, karena kelompok ini sering dipandang sebagai kelompok sesat dan di luar Islam, maka kekhilafahan Ahmadiyah sering tak diperhatikan oleh umat Islam lain.
Tulisan ini secara lebih khusus akan melihat sistem kekhilafahan Ahmadiyah dan sekilas perbedaannya dengan sistem kekhilafan Islam yang lain. Beberapa pertanyaan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana sistem khilafah Ahmadiyah itu terbentuk dan bagaimana cara memilih khalifah? Apa dasar otoritas dari khalifah dan apa batas kekuasaan yang dimilikinya? Apakah ada batasan masa kekuasaan dari seorang khalifah? Kekhilafahan Ahmadiyah, yang menjadi bahasan utama tulisan ini, diangkat untuk memberikan bayangan perbandingan tentang wujud dari sistem khilafah itu ketika diterapkan oleh kelompok Islam di masa kontemporer. Tentu saja akan terjadi berbagai variasi ketika sistem khilafah diterapkan oleh umat Islam yang berbeda, namun ada elemen yang sama dalam semua sistem khilafah, diantaranya adalah adanya bayangan tentang persatuan seluruh umat Islam dibawah satu khalifah dan adanya otoritas keagamaan yang luar biasa pada diri khalifah.
Penutupan lokalisasi tersebut berkait kelindan dengan beberapa isu, diantaranya adalah: ekonomi,pembangunan dan tata ruang kota, moralitas, serta kesehatan masyarakat. Dalam hal ekonomi dan pembangunan kota, Pemkot Surabaya berencana untuk meningkatkan nilai ekonomi kota melalui pembangunan jalan, kawasan perdagangan dan pusat industri rumah tangga yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan mengenai wilayah Dolly dan Jarak. Secara moral, adanya lokalisasi dianggap merusak tatanan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Sedangkan secara kesehatan masyarakat, lokalisasi dianggap sebagai pusat penularan penyakit kelamin.
Lokalisasi merupakan tempat suatu kota atau desa yang bertemakan seksualitas. Jasa yang ditawarkan di lokalisasi bisa beragam, tidak hanya terbatas pada bentuk prostitusi atau PSK. Beberapa bisnis lain yang berada di kawasan lokalisasi adalah panti pijat, perdagangan alat untuk seks, salon kecantikan, pub dan minum-minuman keras dan tempat parkir. Meskipun disebut sebagai lokalisasi, namun semua lokalisasi di Surabaya secara lokasi tidak terpisah dari perumahan penduduk. Tidak ada tembok yang memisahkannya dengan masyarakat sekitar. Bahkan lokalisasi itu tidak jauh dari beberapa Sekolah Dasar (SD), musholla, masjid dan gereja. Tempat tinggal PSK dan keseluruhan aktivitasnya pun menyatu dengan masyarakat sekitar. Jika mengacu pada definisi lokalisasi, maka "Berbagai tempat prostitusi di Surabaya tidak bisa disebut sebagai lokalisasi". Tempat yang dapat dikatakan sebagai lokalisasi adalah Kramat Tunggak di Jakarta yang kini telah ditutup.
Dengan mengacu pada teori Lavebvre, maka lokalisasi di Surabaya itu terjadi dengan sendirinya sebagai tempat orang untuk mempresentasikan dirinya (space of representation), bukan sebagai tempat yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan atau kegiatan tertentu (representation of space). Lokalisasi itu terbentuk dengan sendirinya melalui aktivitas sehari-hari yang dimulai dari satu wisma yang kemudian berkembang terus menjadi banyak. Ini yang disebut Lavebvre sebagai proses pemaknaan space atau the production of space.
• Of these two mainstream organizations, Muhammadiyah is often perceived to be the more conservative one. This organization is seen to be closer and showing more affinity to Islamist groups. On political issues, for instance, Muhammadiyah was still steered by Islamist imagery of the ruling based on religion or the dominance of Muslim in Indonesia.
• Despite several efforts to introduce new perspectives, on cultural issues, Muhammadiyah is often guided by its old principle on the enmity towards, what is called, the TBC (takhayul, bid’ah and churafat; delusions, religious innovation without precedence in the Prophetic traditions and the Qur’an, and superstitions or irrational belief). This position has placed Muhammadiyah in an uneasy relationship with local culture and also traditionalist Islam.
• The three issues that occurred in 2017 --the banning of the HTI, the recurrent controversy on the PKI, and the ruling of the Constitutional Court on Penghayat Kepercayaan-- fall within the cultural spectrum of Muhammadiyah’s standing. They are the issues where Muhammadiyah has a shaky position, becoming easily drawn into Islamist and conservative tendencies.
• Despite the conservative political and cultural accusation, Muhammadiyah does not change from its raison d’être as a social movement with strong emphasis on social services and guided by its long-held theology of al-Mā`ūn (kindness).
• It is the theology of al-Mā’ūn that has been able to prevent Muhammadiyah from dwelling on mythical or abstract issues and neutralize Muhammadiyah from Islamist inclination. It brings the members of Muhammadiyah to become more realistic in seeing the world, distance themselves from the utopic vision of caliphate, the dream of sharia as the Messiah that will solve every problem, or the temptation to create an Islamic state.
• The theology of al-Mā’ūn has directed Muhammadiyah into adopting “pragmatic Islamism”. It is an Islamism that communicates with the dynamics in society or which experiences social dynamics.
● Undermining the teachings and ideology of radicalism seems to be more complicated than direct armed confrontation. Killing terrorist does not always mean killing terrorism. It could even have the opposite impact, i.e. strengthening and fertilizing the radical ideology. It is for the purpose of countering the ideology of terrorism and domesticating radicalism that the government supported NU (Nahdlatul Ulama) in promoting Islam Nusantara, widely believed to be the ideological antidote for radicalism and terrorism.
● Proponents of Islam Nusantara believe that radical ideology is against the characters of Islam Nusantara, i.e. peaceful, smiling, tolerant, moderate, and accommodative to culture. The radical and intolerant ideology are commonly seen in NU circle as brought and disseminated by trans-national movements, such as Hizbut Tahrir and Salafi-Wahhabi groups. They are not terrorist groups, but they teach intolerant and exclusive religiosity which provide a breeding ground for terrorism.
● Within Indonesian Muslims, including NU, Islam Nusantara has received various responses and resistance. The emergence of NU Garis Lurus and the concerted efforts to debunk Islam Nusantara by some preachers are among the forms of activities to undermine Islam Nusantara.
● The introduction of Islam Nusantara is further hampered by the attitude of some of its proponents who emphasize the exclusivity of this brand by identifying Islam Nusantara only with NU and neglecting other Islamic movements. Sometimes, they tend to become reductionist and revisionist in seeing Indonesian Islamic history.
● Barring its current limits, Islam Nusantara has a potential to become an exceptional Islam or a template of tolerant Islam that can be emulated by other Muslims in the world. This particularly with its ability to accommodate local culture and to live in a multicultural society.
Proses perpindahan dari keyakinan keagaman tertentu ke keyakinan lain, menurut William James, pakar psikologi ternama dari Amerika Serikat yang hidup tahun 1842 – 1910, disebut sebagai proses conversion. Proses ini tidak melulu berarti perpindahan dari agama tertentu ke agama lain seperti dari Kristen ke Islam dan dari Hindu ke Kristen, tapi juga mencakup perpindahan dari kelompok agama tertentu ke kelompok agama lain, seperti dari Sunni ke Syiah dan dari Jesuit ke Mormon. Bahkan, perpindahan dari seorang yang sebelumnya merupakan penganut agama atau beriman menjadi seorang ateis atau sebaliknya adalah termasuk dalam kategori conversion.
Pertanyaannya, apakah perpindahan dari seseorang yang secara kultural adalah pengikut NU (Nahdlatul Ulama) menjadi aktivis Muhammadiyah bisa disebut sebagai proses konversi juga? Jika mengikuti William James, maka jawaban dari pertanyaan adalah bisa “ya” dan bisa juga “tidak”. Ini tentu mengacu pada definisi dari kata konversi itu sendiri. Dalam buku klasiknya yang berjudul The Varieties of Religious Experience (1985), William James mendefinikan konversi sebagai sebuah proses dimana “religious ideas, previously peripheral in his consciousness, now take a central place, and that religious aims form the habitual centre of his energy” (h. 196). Artinya, konversi itu terjadi jika suatu pandangan keagamaan yang dulunya hanya dianggap pinggiran dan tak penting atau bahkan menyimpang oleh seseorang, namun kemudian ia berubah menjadi meyakini bahwa yang pinggiran itu menjadi sentral atau sangat penting, maka orang itu telah mengalami apa yang disebut proses konversi. Apalagi jika keyakinan baru menjadi tempat ia menumpahkan seluruh aktivitas dan energinya.
Mengikuti definisi yang dikembangkan oleh James itu, maka beberapa kasus perpindahan dari NU ke Muhammadiyah atau sebaliknya bisa masuk kategori konversi dan bisa juga sekadar perpindahan organisasi. Arifin Ilham, da’i selebritis dan pelopor dzikir berjamaah, bisa menjadi contoh konversi model ini. Ia berasal dari keluarga Muhammadiyah dan mendapat pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Pada masa mudanya Arifin Ilham adalah orang yang benci dan antipati terhadap dzikir. Ia, misalnya, pernah mengatakan kepada orang-orang yang berdzikir bahwa “Mereka itu ahli neraka. Zikir pake dikerasin segala, ramai-ramai lagi” (Mintarja 2004, 41). Namun kini Arifin Ilham menjadi orang yang memilih dzikir sebagai paradigm hidup dan sesuatu yang paling sentral dalam hidupnya. Contoh sebaliknya, konversi dari non-Muhammadiyah ke Muhammadiyah, barangkali bisa dilihat dari kasus Ketua Umum Muhammadiyah saat ini, yaitu Din Syamsuddin.
Berbeda dari kasus Arifin Ilham, banyak sekali orang yang menjadi Muhammadiyah karena dia diangkat menjadi guru atau dosen atau tenaga medis di lembaga milik Muhammadiyah. Ada juga yang menjadi Muhammadiyah karena sekolah di Muhammadiyah. Tentu saja tak semua orang itu bisa disebut mengalami konversi. Mereka yang tak mengalami transformasi spiritual tak akan masuk kategori konversi. Mereka masuk kategori kedua, yaitu hanya “menjadi” (becoming) Muhammadiyah. Beberapa diantara mereka bisa jadi sama sekali tak memahami ideologi Muhammadiyah dan secara ritual berbeda dari apa yang umum dilakukan di Muhammadiyah. Kelompok ini barangkali tak perlu dipermasalahkan selama mereka tetap profesional dalam pekerjaannya dan tidak mengganggu aktivitas Muhammadiyah.
Yang merepotkan adalah mereka yang ada di dalam amal usaha Muhammadiyah namun tak pernah menjadi Muhammadiyah dan justru sebaliknya mereka menjadi ancaman bagi Muhammadiyah. Kelompok ketiga ini mungkin bisa disebut sebagai “Muhammadiyah palsu” atau “fake Muhammadiyah”. Kasus tahun 2006 dan 2007 ketika Muhammadiyah melakukan “disiplin organisasi” dengan mengeluarkan SK 149/2006 dan SK 101/2007 bisa menjadi contoh (Burhani 2013). Tentu saja ada berbagai alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Kita tak hanya perlu menengok hal ini sebagai ancaman dari luar, tapi juga bisa dilihat sebagai kekurang berhasilan proses pengkaderan di internal Muhammadiyah.
Bentuk terakhir adalah mereka yang tidak sekadar “menjadi Muhammadiyah”, tapi “menjadi aktivis Muhammadiyah” namun dengan tetap membawa gerbong pemahaman dan pemikiran yang sebelumnya dimiliki oleh orang tersebut. Mereka yang masuk dalam kategori ini sangat banyak dan, meminjam istilah dari Abdul Munir Mulkhan dan Abdul Mukti, mereka inilah yang kemudian menjadi dasar dari kelompok yang disebut sebagai Marmud (Marhaen-Muhamadiyah), MuNU (Muhammadiyah-NU), Kris-Muha (Kristen-Muhammadiyah), dan sebagainya. Keberadaan kelompok ini bisa memperkaya warna Muhammadiyah dan menghidupkan gerakan pemikiran di organisasi ini jika dikelola dengan baik. Dan tentu saja jika Muhammadiyah ingin menjadi organisasi yang kosmopolit, ia harus siap menerima orang dengan latar belakang yang sangat beragam.
Karena Din Syamsuddin tidak lagi menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka barangkali ini saat yang tepat untuk membicarakan legacy atau karya unggulan yang ia wariskan kepada organisasi modernis terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang berdiri tahun 1912 ini. Tentu saja ada catatan yang sering disebut sebagai kekurangannya selama sepuluh tahun (2005-2015) memimpin Muhammadiyah, misalnya kurang berhasilnya organisasi ini dalam menempatkan kader-kader terbaiknya dalam birokrasi pemerintahan. Namun tulisan ini khusus melihat apa saja warisan dan prestasi dari Din Syamsuddin yang patut dilanjutkan oleh para penerusnya di Muhammadiyah.
Globalisasi sering dipahami sebagai proses penyatuan dunia dimana waktu, jarak dan tempat bukan lagi persoalan dan ketika setiap hal dan setiap orang di bumi ini terkait satu sama lain. Ada empat pergerakan utama dalam globalisasi, yaitu: barang dan layanan, informasi, orang, dan modal. Perpindahan keempat hal tersebut dari satu negara ke negara lain memang telah terjadi sejak dahulu kala. Namun perpindahan dengan sangat cepat hanya terjadi setelah revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi pada beberapa dekade belakangan ini. Akibat dari revolusi itu, dimensi jarak dan waktu menjadi semakin kabur dan sedikit demi sedikit menghilang.
Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini menyebabkan masyarakat secara mudah mengakses informasi dari luar ataupun berinteraksi secara intens dalam sebuah ruang global. Ketika ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) mendeklarasikan kekhilafahan dibawah Abu Bakar al-Baghdadi, kita dikejutkan dengan adanya sejumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan mereka di Timur Tengah dan sebagian dari mereka merekrut anggota di Indonesia serta melakukan baiat di UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta. Ketika konflik Sunni dan Syiah terjadi di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti-Syiah seperti dalam bentuk ANNAS (Aliansi Nasional Anti-Syiah).
Globalisasi juga menyebabkan Trans-National Capitalist Network (TNC) masuk dalam kehidupan masyarakat dan menyedot kekayaan yang mestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Bekerjasama dengan ‘komprador’, para kapitalis global itu menciptakan jurang yang begitu lebar antara mereka yang kaya dan miskin seperti terjadi di daerah penambangan Freeport di Papua.
Filosofi yang mendasari globalisasi adalah asimilasionisme. Dalam filosofi ini, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Makanya, dalam globalisasi budaya, salah satu dampaknya adalah homogenisasi. Ini, misalnya, terwujud dalam bentuk McWorld atau McDonaldization. Contoh lainnya adalah memandang Islam secara homogen dengan mengidentikkannya dengan Arab dan Arabisasi.
Islam Nusantara
Homogenisasi ini tentu tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Respon balik atau resistensi terhadap homogenisasi ini diantaranya dalam bentuk indigenization. Islam Nusantara yang dipopulerkan anak-anak NU dan menjadi tema Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus nanti adalah satu bentuk respon terhadap globalisasi dengan melakukan indigenisasi.
Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu kepada Islam ala Indonesia yang otentik; langgamnya Nusantara, tapi isi dan liriknya Islam; bajunya Indonesia, tapi badannya Islam. Ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan “pribumisasi Islam” yang pernah dipopulerkan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan resmi nama ini diantaranya adalah dalam Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 26 tahun 2008.
Munculnya Islam Nusantara adalah bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai “paradoks globalisasi”. Dalam istilah TH Erikson (2007, 14), “Semakin orang mengglobal seringkali dia menjadi semakin terobsesi dengan keunikan budaya asalnya.” Dalam kalimat ilmuwan lain, “ketika dunia semakin global maka perbedaan-perbedaan kecil antar umat manusia itu semakin ditonjolkan” (Ang 2014, 10). Banyak yang menduga bahwa semakin kita mengenal dunia luar dan kelompok yang berbeda, maka kita menjadi semakin terbuka. Namun seringkali yang terjadi tidak sejalan dengan logika itu. Di tengah globalisasi, banyak orang yang semakin fanatik dan tidak menerima perbedaan serta pluralitas. Ini misalnya terjadi dalam beberapa pilkada yang “mengharuskan” putra daerah yang dipilih. Dalam konteks dunia, justru di era globalisasi ini hampir setiap tahun kita melihat kemunculan negara baru dalam keanggotaan PBB.
Tentu saja respon terhadap globalisasi dalam bentuk “Islam Nusantara” adalah pilihat terbaik dibandingkan dengan penolakan total atau penerimaan total. Dalam merespon terhadap globalisasi, terutama yang datang dari Barat, beberapa kelompok agama justru mencari perlindungan dalam homogenitas dan eksklusivitas kelompoknya. Sepertinya kedamaian itu bisa terjadi dengan menolak keragaman atau sesuatu yang asing. Di tengah globalisasi, banyak orang yang mencoba menutup diri dan menghalangi orang yang berbeda hadir di tengah masyarakat. Fenomena munculnya perumahan atau cluster perumahan eksklusif untuk komunitas agama tertentu adalah misal. Bahkan kuburan/ pemakaman dan rumah kos pun kadang dibuat untuk pengikut agama tertentu. Respon terhadap globalisasi yang lebih buruk lagi tentu saja seperti dalam bentuk redikalisme dan terorisme. Islam Nusantara bisa menjadi respon yang sangat baik terhadap globalisasi jika ia tidak mengarah kepada parokhialisme dan sektarianisme.
Islam Berkemajuan
Respon lain terhadap globalisasi ditampilkan oleh Muhammadiyah dengan slogan “Islam berkemajuan”. Sebelum tahun 2009, slogan ini jarang terdengar bahkan di kalangan Muhamadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul Islam Berkemajuan: Kyai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kyai Syuja’ (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kyai Dahlan ini diantaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah. Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah “Islam berkemajuan”. Pada Muktamar di Yogyakarta tahun 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter ke-Islaman Muhammadiyah.
Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai “Islam kosmopolitan”, yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional” (Tanfidz Muhammadiyah 2010, 18). Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur-tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang otentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan karakter Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana bagi untuk dialog antar peradaban.
Ringkasnya, kelahiran dari slogan “Islam Nusantara” dan “Islam berkemajuan” memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada tahun 1920-an. Ketika itu, sebagai respon terhadap berbagai peristiwa di Arabia dan Turki (comite chilafat dan comite hijaz), maka lahirlah NU. Sementara Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi Kristen, pemikiran Abduh, dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam Déjà vu.
Sebagai sebuah sistem pemerintahan, khilafah telah hancur pada Maret 1924 setelah sistem ini berjalan lebih dari 13 abad semenjak wafatnya Nabi Muhammad tahun 632 Masehi. Namun sebagai wacana, gagasan untuk membangun kembali khilafah itu terus muncul dalam tubuh sebagian umat Islam. Tahun 2007 lalu, misalnya, Universitas Meryland mengadakan survey terhadap 4.384 orang Islam di empat negara (Maroko, Mesir, Pakistan, dan Indonesia). Salah satu pertanyaannya adalah pandangan mereka tentang khilafah. Mereka yang memberikan jawaban “sangat setuju” (agree strongly) dan “agak setuju” (agree somewhat) adalah sebagai berikut: Mesir (67%), Indonesia (49%), Maroko (71%), dan Pakistan (67%). Selain HT dan Al-Qaida, salah satu promoter wacana khilafah adalah Abul A’la Maududi (1903-1979) yang, misalnya, menyebutkan bahwa khilafah adalah salah satu dari tiga prinsip politik Islam, yaitu tauhid, risalah (kenabian), dan khilafah (Maududi tt.; Liebl 2009, 373-4).
Dalam wacana tentang khilafah ini, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kalau Ahmadiyah diakui sebagai bagian dari Islam, maka sistem kekhilafahan Islam itu sebetulnya tidaklah benar-benar hancur. Ini karena sebelum kekhilafahan Turki Utsmani dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk, pada tahun 1908 kelompok Ahmadiyah telah mendirikan kekhilafahan baru di India. Hanya saja, karena kelompok ini sering dipandang sebagai kelompok sesat dan di luar Islam, maka kekhilafahan Ahmadiyah sering tak diperhatikan oleh umat Islam lain.
Tulisan ini secara lebih khusus akan melihat sistem kekhilafahan Ahmadiyah dan sekilas perbedaannya dengan sistem kekhilafan Islam yang lain. Beberapa pertanyaan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana sistem khilafah Ahmadiyah itu terbentuk dan bagaimana cara memilih khalifah? Apa dasar otoritas dari khalifah dan apa batas kekuasaan yang dimilikinya? Apakah ada batasan masa kekuasaan dari seorang khalifah? Kekhilafahan Ahmadiyah, yang menjadi bahasan utama tulisan ini, diangkat untuk memberikan bayangan perbandingan tentang wujud dari sistem khilafah itu ketika diterapkan oleh kelompok Islam di masa kontemporer. Tentu saja akan terjadi berbagai variasi ketika sistem khilafah diterapkan oleh umat Islam yang berbeda, namun ada elemen yang sama dalam semua sistem khilafah, diantaranya adalah adanya bayangan tentang persatuan seluruh umat Islam dibawah satu khalifah dan adanya otoritas keagamaan yang luar biasa pada diri khalifah.
- Indonesia’s 2019 presidential and vice-presidential candidate nominations were finalized on Friday, 10 August 2018. President Joko Widodo’s choice of Ma’ruf Amin as his running mate has brought mixed responses from among Jokowi’s supporters, and a dilemma for religious minorities.
- Ma’ruf Amin is the supreme leader (rois ‘am) of NU (Nahdlatul Ulama), the country’s largest Muslim organisation which is typically viewed as a champion of moderate Islam.
- Ma’ruf Amin was however also an important figure behind the controversial fatwas against Ahmadiyah, and against Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), which led to conservative and radical Muslims’ discriminatory actions against the former and the imprisonment of the latter.
- By settling for Ma’ruf Amin as his running-mate, Jokowi hopes to strengthen his candidacy’s Islamic credentials and win the votes of the conservative and moderate Muslims. Yet, it is not at all clear that Ma’ruf’s candidacy will attract conservative votes.
- The future of religious tolerance and harmony may be at risk. If Jokowi wins next year, the President will have to curb Ma’ruf Amin’s conservative religious inclinations to prevent religious minorities such as Ahmadiyah and Shiah from experiencing even more repressive treatment at the hands of the state.
Kutipan itu sebetulnya adalah sebuah nasehat dari orang tua dan guru bangsa yang pernah hidup di zaman penjajah, Orde Lama, Orde Baru, dan juga Era Reformasi. Sebagai simpatisan berat Masyumi, Buya adalah orang pernah mengalami hidup dalam sengitnya pertarungan politik dan sosial antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan Partai-partai Islam. Karena itu ia juga pernah menjadi penentang keras PKI dan bahkan menyebut masa lalunya sebagai “fundamentalis” dan bagian dari kelompok “garis keras” (Maarif 2009). Hal yang sangat mengejutkan dari postingan tersebut adalah berbagai komentar dan respon yang muncul.
Ada yang mengecam Buya dengan beragam istilah yang sangat kasar, ada yang mengutuk dan melaknat, dan ada juga yang menuntut kepada Muhammadiyah untuk bersikap terhadap Buya. Beberapa diantaranya perlu disebutkan di sini untuk melihat seperti apa ekspresi orang terhadap tokoh sekaliber Buya yang memberikan nasehat tentang sejarah Indonesia. Mulai dari sebutan “orang tua gila”, “pembela penista”, “si tua”, “sudah bau tanah”, “kecebong”, “koplaxx”, “antek”, “tai kucing”, “semakin tua semakin sesat”, “si pikun utek liberal”, “kerak neraka”, “cari makan”, “dasar orang tua… tobat orang tua”, “semakin tua semakin kehilangan akal”, “agen PKI kedok ulama”, “intelek kok guoblok”, “ulama syu’”, “berbicaranya lantang, tapi telinganya tuli, pandanganya buta”, dan juga sebutan yang sudah sering dialamatkan kepadanya, yakni “liberal”.
Sementara mereka yang menuntut agar Muhammadiyah menghukum Buya menyebutkan bahwa Buya adalah “tokoh Muhammadiyah paling mengecewakan”, “mamalukan Muhammadiyah”, dan orang yang tidak bisa menjaga diri, terutama terkait dengan “mulutnya tidak beradab”. Permintaan kepada pimpinan Muhammadiyah juga berupa peninjauan “keberadaan Syafii Maarif di lingkaran para tokoh muhammadiyah” dengan alawan bahwa opininya “lebih sering menyesatkan umat”. Tuntutan pribadi yang agak ringan adalah meminta agar Buya bertobat, atau meminta orang lain agar tak lagi memanggilnya buya karena tak pantas lagi dengan sebutan itu, atau meminta Buya sekolah lagi biar pintar. Ada juga yang berdoa agar Buya mendapat hidayah dan dijauhkan dari virus pluralisme atau berdoa agar Buya husnul khatimah.
Tentu saja ada yang mencoba mendudukkan persoalan dengan melihat dan membaca secara seksama kalimat-kalimat yang disampaikan Buya itu dan meminta jangan saling kecam serta menjaga tatakrama terhadap orang tua. Dukungan, pembelaan, pujian dan doa agar Buya diberi kesehatan dan panjang umur juga bisa ditemukan dalam berbagai komentar.
Berkaitan dengan fanpage itu sendiri, ada sejumlah follower (sekitar 30 orang) yang lantas keluar atau memblokir fanpage tersebut. Ada yang mengancam admin agar tidak bertindak macam-macam. Ada yang menuduhnya liberal, bagian dari JIMM, corong Buya atau “antek syafii”, dan bahkan ada menganggap fanpage itu sebagai infiltrasi dari NU (Nahdlatul Ulama) untuk memecah Muhammadiyah. Namun tampaknya jumlah yang keluar dan memblokir itu sebetulnya jauh lebih kecil daripada jumlah yang menjadi follower baru. Ini bisa dilihat dari jumlah follower yang mengalami kenaikan cukup banyak dibandingkan dengan sebelum adanya posting itu. Mengambil sikap atau keberpihakan dalam kasus-kasus yang membelah masyarakat itu memang bisa menaikkan jumlah followers atau likers. Ini yang membuat sebagian aktivis sosial media menikmati sikapnya yang sektarian.
Kasus seperti ini sudah kesekian kali terjadi. Sebelumnya kontroversi yang heboh terjadi ketika memasang foto Joko Widodo mengimami sholat warga Muhammadiyah. Kemudian, kontroversi kembali ramai ketika posting “Muhammadiyah garis lucu” keluar. Bagi Buya sendiri, ini tentu bukan pertama kalinya mendapat bully sedemikian rupa. Ketika Buya menulis beberapa artikel terkait Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), ia juga mendapat bully dari banyak orang, Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah.
Apa yang bisa dipelajari dari fenomena ini? Pertama, mereka yang berkomentar jahat terhadap Buya itu kemungkinan besar tidak membaca secara utuh tiga tulisan pendeknya tentang PKI di Republika yang berjudul “Isu kebangkitan PKI jadi ritual tahunan” (26/9), “PKI dan kuburan sejarah (1)” (11/7), dan “PKI dan kuburan sejarah (2)” (18/7). Jika mereka membaca dan mencoba memahami, maka akan didapati kesimpulan yang sama sekali berbalik dari tuduhan bahwa Buya sedang membela PKI. Di beberapa bagian dari artikel itu Buya dengan jelas menunjukkan kekejaman PKI dan watak komunisme yang anti-demokrasi dan antikemanusiaan. Buya menegaskan bahwa “rezim komunis tidak pernah ramah kepada kemanusiaan”.
Kedua, mereka yang mem-bully Buya itu hanya melihat kalimat atau kutipan yang dipakai sebagai meme. Kalimat yang merupakan pesan akhir Buya di artikel “PKI dan kuburan sejarah (2)” itu sebetulnya juga memberi keterangan tentang penggunaan isu PKI untuk “tujuan politik kekuasaan”. Sayangnya, kata-kata itu juga tidak diperhatikan. Seandainya yang dikutip dan dibuat meme adalah kalimat “komunisme itu anti-demokrasi dan antikemanusiaan” dan “rezim komunis tidak pernah ramah kepada kemanusiaan”, maka bisa saja ini dipakai sebagi dukungan bagi kelompok yang saat ini mengungkit-ungkit isu PKI untuk tujuan politik. Namun mereka yang sudah benci dan antipati terhadap Buya bisa jadi tak mau melihat itu juga. Mereka sudah benti dan memandang negatif terhadap Buya, apapun yang ia katakan. Ini terlihat dari komentar yang selalu mengaitkan Buya dengan sikapnya terhadap isu Ahok beberapa waktu lalu.
Ketiga, seperti ditulis Merlyna Lim (2017), apa yang dialami Buya adalah contoh dari post-truth politics, dimana kebenaran itu bukan sesuatu yang pertama dan utama. Meski PKI itu sudah tidak ada, namun ketika ia dijual lagi dengan kemasan baru untuk menakut-nakuti rakyat dan dipromosikan sedemikian rupa, maka ia akan terjual juga. Branding baru tentang bahaya PKI dibuat dan di-viralkan. Orang jujur seperti Buya yang dengan baik-baik memberi nasehat lantas di-bully. Sosial media yang pada awalnya disanjung sebagai arena freedom of expression ternyata memiliki efek negatif seperti menurunnya kualitas informasi dan naiknya kebencian terhadap mereka yang berbeda. Upaya tabayyun (merefleksikan dan konfirmasi) terhadap perbedaan dan pertentangan juga sering hilang karena di dunia orang lebih sering bergerombol dengan yang seide (algorithmic enclaves) dan mematikan atau memutus hubungan dengan mereka yang berbeda pandangan.
-oo0oo-
Abstrak
Siapa yang lebih otoritatif dalam melakukan penelitian tentang kelompok minoritas agama tertentu,Insider atau outsider? Bagaimana menerapkan konsep detachment, neutrality, dan bracketing dalam mengkaji kelompok yang oleh mayoritas ulama difatwakan and berbagai ormas keagamaan sebagai aliran sesat seperti Ahmadiyah? Dan bagaimana pula berbagai konsep tersebut dihadapkan dengan metode penelitian lapangan yang disebut dengan going native dan participant observation? Sejauhmana identitas peneliti sebagai non-Ahmadi mempengaruhi penelitian dan penilaian tentang Ahmadiyah? Tulisan ini merupakan refleksi akademik terkait pengalaman penulis dalam mengkaji Ahmadiyah, dalam menerapkan berbagai teori dan prinsip akademik dalam kajian tentang komunitas ini, dan bagaimana penulis bersikap terhadap berbagai konflik individu serta kontroversi seputar isu Ahmadiyah. Tulisan ini didasarkan pada tujuh tahun pengalaman hidup, bergaul, mengkaji, and berpartisipasi dengan beragam aktivitas Ahmadiyah di Indonesia, Singapura, Jepang, India, Inggris, dan Amerika Serikat.
[Terjemah al-Quran versi Ahmadiyah memiliki beberapa karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan terjemah versi Islam sunni pada umumnya. Namun demikian, terjemah seperti di atas, khususnya terjemah al-Quran dalam bahasa Belanda --yang dialih-bahasakan dari The Holy Qur’ān karya Muhammad Ali oleh Soedowo-- cukup berpengaruh di masyarakat muslim Indonesia pada paruh pertama abad ke-20. Bertentagan dengan fatwa dari Muhammadiyah maupun dari Muhammad Rashid Rida yang melarang penggunaan terjemah versi Ahmadiyyah, terjemha Soedewo ini justru menjadi rujukan bagi kalangan terdidik untuk memahami Islam. Tulisan ini secara khusus menjawab pertanyaan: mengapa terjemah al-Quran versi Ahmadiyyah ini cukup berpengaruh di Indonesia, apa yang menarik dari tterjemah ini bagi mereka, serta apa sumbangan pemikiran terjemah ini pada perkembangan keilmuan al-Quran di negeri ini. Menurut penulis, terjemah versi Ahmadiyyah, khususnya yang berbahasa Belanda, mengalami kesuksesan pada masa revolusi dipengaruhi oleh tiga hal: (1) bahasa Belanda yyang dipakai adalah bahasa kalangan terdidik, (2) isinya sesuai dengan kebutuhan kalangan terpelajar yang ingin mencari pemahaman yang harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan, dan (3) terjemah ini merupakan satu-satunya bentuk publikasi modern dari terjemah al-Quran yang ada pada masa itu. Dalam konteks ideologi, penerimaan kaum intelektual ini terutama terkait dengan upaya perlawanan Islam terhadap tekanan misi Kristen dan masuknya ideologi-ideologi anti agama, khususnya materialisme dan atheisme.]
Sebaliknya dari Islam Nusantara, Islam Arab sering diasosiasikan dengan beberapa sifat negatif seperti kekerasan, diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan, tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran heritage dari Makkah dan Madinah, serta cenderung menolak inovasi dalam pemikiran keagamaan. Pandangan ini sering didukung dengan kabar tentang perlakukan terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia), larangan bagi perempuan untuk menyopir, wisata Arab di Puncak, pembangunan Makkah yang mirip Las Vegas, dan tak kunjung usainya perang dan konflik di Timur Tengah. Karena itulah, seringkali didengar penegasan bahwa Islam Indonesia bukanlah Islam Arab. Bahkan, ada juga yang bersikap ekstrem dengan mengekspresikan ketidaksukaan terhadap simbol atau apapun yang berkaitan dengan identitas Arab yang ada di masyarakat.
Problem yang terkait dengan citra buruk Islam Arab itu akan kita singgung nanti, namun inti dari tulisan ini adalah ingin membahas pertanyaan tentang mengapa sebagian orang terlihat begitu antipati terhadap budaya Arab yang ditampilkan di masyarakat? Mengapa pertentangan identitas etnik antara “Islam Pribumi” dan “Islam Asing” sering mengemuka belakangan ini?
Penguatan Identitas
Dalam tulisannya yang berjudul “Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East” (2012) Saba Mahmood, diantaranya, mencoba melihat tentang adanya penguatan identitas dan dampaknya terhadap pertentangan antara “agama pribumi” dan “agama asing” di Mesir. Mahmood menyebutkan bahwa saat ini sebagian orang meragukan identitas dan loyalitas orang Mesir yang memeluk agama Islam. Apakah mereka tetap menjadi orang Mesir yang berakar kuat pada budaya bangsa itu atau telah berubah menjadi orang Arab?
Menjadi Muslim itu pada sebagian orang ternyata tak sekadar perpindahan agama, tapi juga pergantian kultur; mengadopsi budaya Arab, berbahasa Arab, dan berperilaku seperti orang Arab. Bahwa orang Mesir yang menjadi Muslim itu bukan hanya berubah identitas keagamaannya, tapi juga identitas kulturalnya; mereka telah berubah menjadi orang Arab. Karenanya, beberapa orang Qoptik mengklaim bahwa hanya mereka sajalah yang betul-betul menjaga dan memelihara identitas dan kebudayaan Mesir.
Hal yang hampir sama terjadi di Indonesia meski dalam konteks dan relasi yang berbeda. Pertentangan identitas yang berkaitan dengan Arab itu berada pada dua level, yaitu: Pertama, antara folk atau indigenous religions vs. foreign religions (agama leluhur atau pribumi vs. agama asing). Kedua, antara “Islam pribumi vs. Islam asing” atau, jika ditarik pada garis ekstrim, antara “Islam Nusantara vs. Islam Arab".
Pada poin pertama, pertentangan itu terjadi karena agama-agama yang dominan di Indonesia itu ternyata semuanya adalah agama asing. Enam agama yang “diakui” di Indonesia itu bahkan kadang dianggap sebagai agama “penjajah” (invaders) yang kehadirannya telah menggusur beragam agama lokal atau agama leluhur. Bersamaan dengan pengukuhan mereka sebagai agama “resmi” atau “diakui”, berbagai agama lokal itu lantas hanya dianggap sebagai kepercayaan, bukan agama. Mereka tidak dianggap layak atau memenuhi syarat untuk disebut agama yang diberi definisi mengikuti kriteria agama yang dominan.
Pada poin kedua, dalam konteks Islam saja, terdapat perdebatan tentang implementasi ajaran-ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan, tentang universalisme ajaran Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam, tentang dakwah kultural dan pribumisasi, dan lain-lain. Jika dibawa ke hal kongkrit, maka pertanyaanya, misalnya, adalah, “Apakah jilbab merupakan budaya Arab atau ajaran Islam? Apakah jenggot, khitan perempuan, dan baju putih itu merupakan sesuatu yang kultural saja?” Pendeknya, apakah dalam berislam itu kita harus juga mengadopsi budaya Arab atau kita bisa memodifikasinya sesuai dengan kultur dan identitas Indonesia dan menamainya “Islam Nusantara”? Poin kedua ini menjadi isu panas ketika masyarakat sibuk berdebat tentang definisi, metodologi, dan kriteria tentang Islam Nusantara.
Akulturasi dan Segregasi
Kedatangan orang Arab di Indonesia telah terjadi sejak lama. Hubungan mereka dengan pribumi Nusantara juga tidak bisa dikatakan monolitik. Selain itu, ada beragam proses akulturasi budaya yang dilakukan oleh orang Arab ketika tiba di Indonesia. Konon, di beberapa tempat di NTB (Nusa Tenggara Barat), orang-orang Arab tidak mengajarkan Bahasa Arab kepada anak-anaknya agar mereka cepat beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat setempat (Bamualim 2016).
Bahkan, seperti ditulis oleh Michael Feener dalam “Hibridity and the ‘Hadhrami Diaspora’ in the Indian Ocean Muslim Networks” (2004), tokoh-tokoh semisal Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, Yusuf al-Makassary, Abdul Rauf al-Singkeli, adalah beberapa contoh nama dari keturunan Arab yang lebih dikenali dengan identitasnya sebagai orang Indonesia daripada sebagai keturunan Arab, baik di dalam negeri maupun dalam konteks internasional. “Ethnicity... was not a primary factor in the construction of one’s identity for these individuals” (Etnisitas... bukanlah faktor tama dalam pembentukan identitas bagi individu-individu ini).
Menurut kajian Feener, identitas Arab itu baru menguat karena politik Belanda dan dilanjutkan oleh orang-orang Arab sendiri pada awal abad ke-20 ketika merasakan bahwa penguatan identitas itu diperlukan, diantaranya dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan pembaruan pemikiran keagamaan. Belakangan ini, identitas etnis itu kembali menguat seiring dengan globalisasi dan marjinalisasi.
Saya sepakat dengan tulisan Mohamad Shohibuddin (Sindo, 24 Januari 2017) bahwa masyarakat sering terjebak dalam memahami Islam Nusantara, yaitu, “sebagai ekspresi sosio-keagamaan dari kelompok tertentu di Indonesia, dalam hal ini Nahdlatul Ulama” dan bahwa “Islam Nusantara ‘mahjubun bin Nahdliyyin’, yakni dikaburkan oleh kalangan NU sendiri”. Lebih parah lagi, banyak tokoh yang sering memperhadapkan Islam Nusantara dengan Islam Arab sebagai cara mendefinisikan dirinya. Ini tentu bisa memperkuat identitas Islam Nusantara, namun melalui jalur yang negatif. Inilah diantaranya yang juga berkontribusi terhadap terciptanya kebencian terhadap Islam Arab.
Tuduhan terhadap Islam Arab sebagai sumber kekerasan ini sangat mungkin tidak diterima oleh orang Arab atau keturunan Arab di Indonesia. Ini adalah bagian dari stereotyping. Kajian lebih detail tentang ini sedang dilakukan oleh Ermin Sinanovic dari IIIT (International Institute of Islamic Thought) Virginia. Namun, secara ringkas, kutipan dari Azhar Irfansyah dan Muhammad Azka Fahriza (2017, 45) cukup mewakili, “Ada banyak prasangka-prasangka tidak sehat yang dilancarkan terhadap gerakan Islamis. Salah satu yang paling sering dikemukakan di media sosial adalah bahwa gerakan ini tidak pas dengan ekosistem nusantara dan harus diasingkan ke Timur Tengah. Ini pandangan yang sama keblingernya dengan kelompok rasis ultra-kanan Golden Dawn di Yunani, yang menganggap semua kekerasan berasal dari Arab dan harus dikembalikan ke Arab”.
Beruntung, kedatangan Raja Salman membantu mentralisir stereotype negatif tersebut dan bahkan berfungsi melawan citra negatif Arab. Sikap masyarakat terhadap kedatangan Raja Salman dan rombongannya berbeda dari pandangan dan sikap yang seringkali muncul berkaitan dengan Arab. Kunjungan ini menjadi topik utama berita nasional dan umumnya terlihat positif. Pembicaraan bergerak dari persoalan investasi, kerjasama, Wahabisasi, TKI di Saudi Arabia, wisata Arab di Puncak, Arab ori vs. Arab kw, pertemuan dengan Ahok, wisata ke Bali, mobil dan barang perbekalan yang dibawa, tentang Raja Salman sendiri serta keluarganya, dan berbagai topik lain. Beberapa media bahkan menggunakan kunjungan Raja Salman ini untuk menyindir beberapa orang keturunan Arab yang sering dicitrakan dengan kekerasan dan belakangan ingin membakar populisme Islam untuk melawan negara. Maka tema-tema yang diangkat oleh media tersebut dari kunjungan Raja Salman adalah penguatan Islam moderat dan penentangan terhadap terorisme.
Terakhir, perbedaan antara saya dan Shohibuddin dalam konteks Islam Nusantara adalah pada pemahaman tentang makna exceptional Islam. Shohibuddin mendefisikannya sebagai “identik dengan Nahdlatul Ulama (NU)”, maka saya memahaminya sebagai sesuatu yang menjadi sumber pride dan kepercayaan diri. Sebagai exceptional Islam, Islam Nusantara adalah Islam yang unik; bisa beradaptasi secara kultural tanpa kehilangan substansinya sama sekali.
Namun bila melihat beberapa fenomena belakangan ini, seperti berbagai aksi intoleransi terhadap minoritas, mudahnya membully secara berjamaah kepada mereka yang berpandangan berbeda, dan terjadinya konflik keagamaan hanya karena persoalan sepele, maka ada kekhawatiran bahwa Islam moderat di Indonesia itu sudah goyah. Tindakan intoleransi, diskriminasi dan bigotry memang bukanlah masuk kategori terorisme, namun itu bisa menjadi awal dari perilaku yang bisa berujung pada terorisme.
Ancaman melemahnya Islam moderat itu juga bisa dilihat dari penyebaran otoritas keagamaan dengan hadirnya da’i dan muballigh instant, infiltrasi pandangan non-wasathiyya ke NU dan Muhammadiyah, masuknya berbagai gerakan keagamaan trans-nasional dengan agenda yang bertentangan dengan semangat untuk hidup dalam masyarakat majemuk, serta instant-learning agama karena media sosial dan teknologi informasi lain. Jika tak sadar dan waspada, maka kegagalan Islam moderat itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukan sekarang tentunya, tapi jika tak diantisipasi bisa terjadi pada tahun-tahun yang akan datang.
Kekhawatiran itu seperti semakin mendapatkan peneguhan ketika melihat perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat, Filipina, dan Inggris. Amerika yang selama ini dinggap sebagai pusatnya toleransi dan multikulturalisme ternyata secara mengejutkan memilih presiden (Donald Trump) yang sepertinya anti terhadap prinsip-prinsip yang membuat Amerika seperti sekarang ini. Kemenangan kelompok konservatif sedang menyebar di seluruh dunia, baik itu konservatisme Islam, Kristen, maupun agama lainnya. Inilah yang kemudian membuat tulisan ini ingin menyebut fenomena sekarang ini sebagai the triumph of conservatism (kemenangan konservatisme).
Buya Ahmad Syafii Maarif
Salah satu tantangan nyata terhadap otoritas keagamaan tradisional, yang menjadi fondasi bagi Islam moderat, adalah apa yang dialami oleh Buya Ahmad Syafii Maarif. Tokoh yang sejak kecil belajar agama dalam sistem pendidikan Islam di Minangkabau, dilanjutkan dengan sekolah guru di Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan menempuh pendidikan doktoral dalam kajian Islam di Universitas Chicago, tiba-tiba dipertanyakan otoritasnya berbicara agama oleh mereka yang baru kemarin sore belajar Islam. Ini adalah sesuatu yang sangat menggelikan, namun betul-betul terjadi.
Buya Syafii yang selama delapan tahun (1998-2005) dipilih untuk memimpin Muhammadiyah, organisasi modernis terbesar di Indonesia dengan puluhan juta anggota, tiba-tiba dipertanyakan kredibilitasnya dalam memahami Al-Qur’an oleh mereka yang membaca Al-Qur’an pun barangkali belum fasih. Orang-orang yang belajar Islam melalui google, facebook, dan twitter tiba-tiba merasa lebih mengerti Islam daripada imam dari jutaan jamaah Muhammadiyah. Mereka lebih percaya dan menggandrungi kelompok celebrity preachers yang memiliki pengetahuan agama dangkal tapi penampilannya penuh dengan aksesoris dan simbol-simbol agama, atau lebih tepatnya simbol Arab. Mereka bahkan sering menjadikan kelompok “ulama” ini sebagai kiblat dalam beragama.
Fenomena yang dialami oleh Buya Syafii ini oleh Julia Day Howell dianggap sebagai pergeseran otoritas keagamaan dari high-brow (terdidik dan berpengetahuan) ke low-brow (dadakan namun gemerlapan) karena adanya revolusi teknologi informasi, terutama televisi dan media sosial. Yang menjadi daya tarik dari agamawan baru ini bukanlah kedalaman pengetahuan, tapi performance dan entertainment yang didukung oleh media.
Berkaitan dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, tentu saja diakui bahwa ia memudahkan manusia dalam memperoleh data, memberikan akses terhadap sesuatu yang sebelumnya hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Namun kelemahannya, seringkali informasi dan data yang kita peroleh sebetulnya hanyalah yang sesuai dengan keinginan kita. Data yang kita peroleh adalah yang sesuai dengan status yang kita buat, info yang kita cari, dan teman yang kita miliki. Intinya, apa yang kita dapat adalah yang sesuai dengan algoritma pikiran kita selama ini. Sehingga, jika teman-teman kita adalah kelompok liberal atau konservatif, maka info yang lebih banyak masuk tentu saja sesuai dengan algoritma itu. Ini yang membuat orang tanpa mengecek dulu siapa Buya Syafii Maarif dengan mudahnya membagi dan retweet meme-meme jahat tentang Buya.
Menghargai Perbedaan
Diantara ciri Islam wasathiyya (Islam moderat) adalah sikap tasamuh (toleransi), tawazun (berimbang), dan I’tidal (adil). Ini, misalnya, diwujudkan dalam mensikapi dan menghargai perbedaan. Imam Syafii, yang menjadi panutan dalam bidang fikih oleh kelompok Muslim moderat, dikenal dengan qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru) yang menunjukkan kesedian berubah dan menerima perbedaan jika ada argumen yang lebih kuat.
Mengikuti tradisi ulama, pesantren kita memahami betul semboyan qauluna shahih yahtamilul khata', qauluhum khata' lakin yahtamilul shahih (pandangan kita benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Pandangan mereka salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran). Ini adalah refleksi tentang penghargaan terhadap mereka yang berbeda pandangan, termasuk dalam isu-isu yang serius. Tidak main mutlak-mutlakan.
Nilai-nilai moderatisme itu yang belakangan terasa hilang. Karena berbeda pandangan, ada kader Muhammadiyah yang secara kurang tawadhu’ menyebut Buya Syafii bicara “ngelantur”. Ada pula yang memplesetkan Buya menjadi buaya atau menyebutnya “tua Bangka”, “bau tanah”, dan “sudah mau mati”.
Bahkan banyak sekali kata-kata yang lebih parah dan tidak merefleksikan ajaran Islam tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua. Padahal Nabi Muhammad berpesan: laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana (bukanlah bagian dari umatku mereka yang tak menyayangi yang lebih kecil/ lemah/ minoritas dan mereka yang tak menghormati yang lebih besar/ tua/ mayoritas).
Siradj menganjurkan warga NU untuk tidak bergabung dalam Aksi Bela Islam III dan NU bahkan mengeluarkan fatwa bahwa sholat Jum'ah di jalan raya adalah tidak sah. Alih-alih mengikuti anjuran ini, beberapa pesantren di Jawa Barat seperti Ciamis dan Tasikmalaya justru mengirimkan santri-santrinya untuk pergi ke Monas dengan berjalan kaki. Tentu afiliasi keormasan dari pesantren-pesantren itu perlu dilihat kembali. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari warga NU yang bergabung dalam Aksi Bela Islam III.
Apa yang terjadi di NU itu juga terjadi di Muhammadiyah. Anjuran Haedar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kepada warganya untuk tidak turun aksi seperti fall on deaf ears, tak dihiraukan oleh beberapa anggota Muhammadiyah. Alih-alih mengikuti anjuran ketua umumnya, banyak warga NU dan Muhammadiyah yang memilih bergabung dengan Habib Rizieq Shihab, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, Bachtiar Nasir, dan Zaitun Rasmin untuk melakukan aksi yang terpusat di tugu Monas (Monumen Nasional) Jakarta.
Selama ini Habib Rizieq Shihab, jika dianggap sebagai ulama, maka ia adalah bagian ulama pinggiran atau ulama jalanan. Dalam istilah akademik, ia biasanya disebut low-brow ulama dan sering dikontraskan dengan high-brow ulama semisal Quraish Shihab dan Ma’ruf Amin. Amin Abdullah sering menyebut Shihab dan FPI (Front Pembela Islam) yang dipimpinnya sebagai noisy minority (kelompok kecil yang berisik). Bahkan Buya Ahmad Syafii Maarif sama sekali tak menganggap mereka sebagai ulama. Istilah Buya untuk mereka adalah para preman berjubah. Namun Aksi Bela Islam III seakan telah mengubahnya dari orang marjinal dan peripheral menjadi salah satu tokoh nasional.
Rizieq menjadi khatib dalam sholat Jum'at yang berpusat di Monas yang secara tak sengaja dihadiri oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Polkam Wiranto, Panglima TNI Gatot Nurmanto, Kapolri Tito Karnavian, dan pimpinan negara yang lain. Pada hari itu, ia seperti menjadi pimpinan dari jutaan umat Islam Indonesia. Aksi Bela Islam III seperti telah menyulapnya menjadi tokoh yang tak bisa dikecilkan atau diabaikan.
Sebelum Aksi Bela Islam III atau disebut juga sebagai Aksi 212, pemerintah dan juga banyak dari elemen umat Islam bukan hanya tak memandang Habib Rizieq. Pemerintah cenderung mengacuhkan dan mengabaikannya. Jokowi berusaha mengontrol suasana dengan mengundang ulama dari NU, Muhammadiyah, dan MUI untuk datang ke istana negara. Jokowi bahkan mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Menteng dan kantor PBNU di Kramat untuk bertemu dengan pimpinan kedua organisasi tersebut. Ia bahkan membuat peristiwa penting dengan menghadiri penutupan Rakernas Pemuda Muhammadiyah di Tangerang. Namun Presiden mengabaikan atau tidak mau mengadakan pertemuan dengan pimpinan Aksi Bela Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa - Majelis Ulama Indonesia).
Setelah peristiwa 212, Rizieq Shihab dan GNPF-MUI seperti tak ingin kehilangan panggung dan momentum yang telah mengangkat mereka ke panggung nasional. Diadakanlah Aksi Sholat Subuh Berjamaah pada 12 Desember 2016. Mereka juga merancang Aksi Bela Islam IV atau yang dalam beberapa meme disebut sebagai Aksi Lempar Jumrah pada 6 Januari 2017 jika tuntutan mereka agar Ahok dipenjarakan karena dianggap melecehkan Islam tidak terpenuhi.
Berbeda dari NU dan Muhammadiyah yang memiliki berbagai amal usaha semisal rumah sakit, sekolah, dan pesantren yang harus selalu diurus, Shihab dan FPI tidak memiliki lembaga-lembaga semisal itu. Gerakan utamanya adalah melakukan demonstrasi dan sweeping tindakan yang dianggap sebagai maksiat dengan menggunakan semboyah "amar ma'ruf nahi mungkar". Karena tak punya amal usaha, maka tak ada kesibukan yang menyita pikiran dan tenaganya selain untuk aksi demo dan sweeping.
Selama ini dalam melakukan aksi-aksinya, Shihab lebih banyak mendapat kecaman dari masyarakat, termasuk dari umat Islam. Momentum 212 telah mengubahnya dari zero to hero, dari seorang pecundang menjadi pahlawan. Bahkan beberapa meme yang tersebut di media sosial telah mempersonifikasi sosok Shihab seperti sosok Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua dalam sejarah Islam yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Karena itulah, ia ingin terus memelihara momentum tersebut dan membuat gerakan ini terus bergulir atau jika memungkinkan seperti snow ball yang semakin membesar.
Selain Aksi Sholat Subuh berjamaah pada 12 Desember, Shihab dan GNPF juga menjadikan semangat 212 sebagai alat kebangkitan ekonomi umat Islam dengan mengadakan FGD bertema: "Revolusi Ekonomi, Terobosan Ekonomi Umat". Dan masih dengan semangat 212, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang atribut yang berkaitan dengan natal, maka sweeping pun dilakukan oleh anggota-anggota FPI di berbagai toko, swalayan, dan kantor-kantor.
Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan berkaitan dengan Aksi Bela Islam I, II, dan III itu diantaranya adalah: Dalam fragmentasi otoritas ulama sekarang ini, bagaimana kita melihat peran dan posisi NU dan Muhammadiyah? Apakah Rizieq Shihab akan terus memiliki peran lebih besar, pengaruh lebih luas, dan dipandang sebagai tokoh nasional yang diikuti setelah peristiwa ini? Bagaimana dengan peran media sosial dalam penciptaan fragmentasi otoritas keagamaan ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kajian serius. Ini juga merupakan pertanyaan yang menjadi titik tolak untuk melihat keberagamaan di Indonesia pada beberapa tahun mendatang.
Dalam market akademik, sepertinya brand Islam Nusantara lebih menarik daripada Islam Berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah. Setidaknya, baru Syed Khairudin Aljunied (Singapura) yang secara khusus mendalami karakter Islam Berkemajuan atau Islam Kosmopolitan, sebagaimana tertulis dalam bukunya Muslim Cosmopolitanism: Southeast Asian Islam in Comparative Perspective (Edinburgh University Press 2016). Memang, buku ini tidak secara khusus membahas Muhammadiyah. Ia lebih membahas tentang watak kosmopolitan dari Islam di Asia Tenggara yang bisa dipelajari atau bahkan diadopsi oleh umat Islam di negara lain.
Berkaitan dengan Islam Nusantara, ulasan yang dilakukan oleh pengamat asing dan aktivis NU lebih banyak berputar seputar definisi, latar belakang kemunculan, karakter, obyek garapan, manhaj (metodologi), dan implementasinya dalam konteks ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan dunia yang global. Satu hal yang perlu mendapat elaborasi lebih dan menjadi fokus dari tulisan ini adalah geneologi dari Islam Nusantara itu sendiri dan peran Gus Dur terhadap lahirnya identitas ini.
Secara geneologi, terdapat tiga tahapan penting dari pembentukan Islam Nusantara setelah kemerdekaan. Tahap pertama adalah apa yang terjadi tahun 1950 dan 1960-an ketika para sarjana asing melihat Islam di Indonesia sebagai distinctive Islam atau Islam yang beda (dari Timur Tengah atau tempat lain). Namun distingsi di sini lebih banyak mengacu kepada makna negatif, yaitu superficial Islam dan peripheral Islam (Islam pinggiran). Islam di Indonesia dianggap sebagai pinggiran tidak hanya karena secara geografis Indonesia terletak di pinggiran dunia Islam, tapi juga dari segi substansi dan kualitas umat Islam Indonesia itu dianggap belum memeluk Islam secara sempurna. Keislaman mereka hanyalah superficial. Islam hanya menjadi lapisan tipis dari keyakinan keagamaan yang merupakan gabungan dari animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha.
Pendeknya, orang Islam Indonesia ketika itu dianggap hanya memeluk corrupted Islam atau Islam yang telah tercemar atau Islam yang tidak murni atau Islam yang tak sempurna. Inilah pemahaman beberapa pengamat asing tentang Islam Nusantara pada tahun-tahun awal Indonesia.
Tahap kedua adalah formation of identity atau pembentukan identitas Islam Nusantara. Ini terjadi tahun 1980 dan 1990-an dengan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai tokoh yang paling penting. Pribumisasi Islam yang ditawarkan oleh Gus Dur adalah pembalikan terhadap berbagai stigma negatif yang dialamatkan kepada Islam di Indonesia atau Islam Nusantara.
Gus Dur membangunkan keyakinan diri umat Islam Indonesia bahwa keyakinan keagamaan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai heterodoks (menyimpang) itu sebetulnya tidak kalah ortodoknya dengan Islam yang ada di pusat Islam di Mekah dan Madinah. Bahwa Islam di Indonesia itu sama otentiknya dengan Islam di Saudi Arabia atau negara lain. Jika sebelumnya terdapat anggapan bahwa keramahan orang Indonesia itu karena mereka memeluk corrupted Islam, maka dengan pribumisasi Gus Dur ingin menunjukkan bahwa keramahan itu muncul karena mereka memeluk Islam yang otentik. Gus Dur menunjukkan bahwa Islam Indonesia yang damai, merayakan pluralitas, selaras dengan demokrasi, dan sesuai dengan HAM (Hak Asasi Manusia) itu bukan berangkat dari ke-Islaman yang sinkretik, namun itulah esensi dari Islam.
Singkatnya, Gus Dur membangun sebuah identitas Islam Indonesia yang berbeda dari pengamatan orang asing semisal Clifford Geertz, L.M. Penders, dan Snouck Hurgronje. Tahun 1980-an juga menjadi tahun awal dari kebangkitan kaum nahdliyyin dan lebih percaya diri dengan model ke-Islamannya.
Tahap ketiga adalah yang terjadi belakangan ini, terutama pasca Muktamar NU di Jombang tahun 2015. Memang, istilah Islam Nusantara sudah dipakai oleh Jurnal Tashwirul Afkar pada edisi no. 26 tahun 2008. Istilah itu juga sudah dipakai oleh Azyumardi Azra dalam bukunya Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (2002) yang merupakan terjemahan dari buku Historical Islam: Indonesian Islam in Global and Local Perspective.
Namun demikian, istilah Islam Nusantara yang dipakai NU saat ini memiliki makna khusus yang berbeda dari pemakaian sebelumnya. Nusantara di situ tidak hanya mengacu kepada tempat, tapi juga keberagamaan tertentu. Menurut pengamatan saya, Islam Nusantara bahkan dipahami lebih dari sekadar identitas sebagaimana yang terjadi pada masa Gus Dur, tapi ini menunjukkan sebuah exceptionalism.
Islam Nusantara adalah sebuah kekhasan atau keunikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ini bukan hanya karakter ataupun manhaj, tapi sebuah spirit dan penggerak dari sebuah perubahan. Spirit ini mungkin bisa disandingkan dengan American exceptionalism yang sebanyak apapun kritik terhadapnya, orang Amerika banyak yang tetap meyakini bahwa mereka dan negara mereka adalah exceptional. Inilah yang terjadi pada Islam Nusantara versi NU. Ini yang dirasakan secara luas oleh orang NU. Makanya, banyak orang yang kemudian cemburu dan ingin tahu tentang identitas ini.
Persoalannya sekarang adalah apakah ke-Islaman yang exceptional ini mampu berhadapan dengan gelombang konservatisme yang sedang terjadi di Indonesia? Apakah NU bisa terus menguri-uri keunikannya dan menampilkannya sebagai identitas di tengah kompetisi dengan berbagai gerakan Islam trans-national atau tarikan untuk bersikap sektarian seperti yang terjadi di Sampang Madura. Harapannya adalah keyakinan diri yang tinggi itu terus tumbuh dan Islam Nusantara bisa menghadapi wabah populisme yang menggejala di dunia.
Anies Baswedan’s Arabic ancestry aided him in this election. Incumbent governor Ahok’s Chinese minority status was clearly detrimental.
The rise of identity politics challenges democratic Indonesia’s efforts to manage its ethnic and religious diversity.
Arabic ancestry may prove detrimental for political candidates in upcoming elections, particularly against pribumi candidates.
On 19 July 2017, the government issued the regulation in lieu of law (Perppu) No. 2/2017 and then revoking the legal status of HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), a conservative Islamist group deemed to threaten Pancasila, the state ideology.
This regulation could therefore help President Jokowi win the battle against conservative Islamist groups and domesticate them. Moderate Islam can win this contest of belief with the help of the government. The rise of religiosity can be retarded and curbed with government intervention rather than open competition between various religious groups.
Although this policy was supported by mainstream Muslim organizations, the regulation’s doing away with court approval and administrative sanctions before disbanding offending organizations harks back to authoritarian policies of the New Order.
The broadly phrased regulation can be abused to ban any organization, such as religious minorities, deemed threatening to the values of Pancasila.